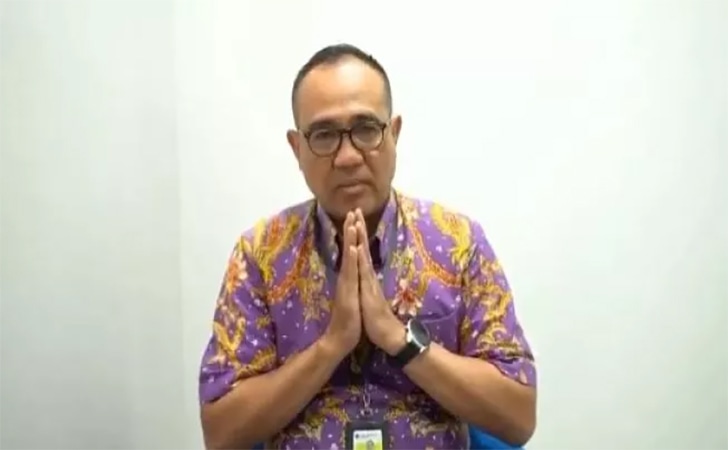Oleh: Ahmad Zazali, SH., MH.
Praktisi Sosio Legal dan Resolusi Konflik di AZ Law Office & Conflict Resolution Center
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Manusia sebagai Mahluk Sosial. Manusia telah ditakdirkan sebagai mahluk yang paling sempurna oleh Tuhan dibandingkan dengan mahluk ciptaanNya yang lain. Sehingga tidak heran jika manusia lebih menentukan dan dominan dalam menentukan relasi sosial dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar atau lingkungan.
Karena itu, Aristoteles mengkategorikan manusia masuk ke dalam kategori “Zoon Politicon” yang berarti manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Oleh karena sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial.
Namun demikian, dibalik kesempurnaan manusia sebagai mahluk sosial, dalam pandangan Islam manusia secara etimologi disebut juga insan yang memiliki sifat lupa dan jinak.
Manusia juga selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru disekitarnya. Keberadaan manusia sangat nyata sekali berbeda dengan
makhluk yang lainnya. Seperti dalam kenyataannya manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kakidan memiliki kemampuan untuk berfikir. Berfikir merupakan sifat dasar dari manusia yang menentukan hakekat manusia itu sendiri dan mebedakannya dengan makhluk lainnya.
Interaksi sosial sesama manusia dan dengan lingkungannya, menurut Koentjarainingrat, terdapat keanekaragaman pranata-pranata sosial antara orang satu dengan yang lainnya dalam sebuah komunitas. Terdapat delapan macam pranata sosial, yaitu sebagai berikut:
Pertama, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya keluarga.
Kedua, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian, misalnya
pertanian.
Ketiga, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti lembaga-lembaga
pendidikan.
Keempat, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, misalnya ilmu
pengetahuan.
Kelima, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohani-batiniah dalam menyatakan rasa keindahan dan rekreasi, misalnya seni rupa, seni lukis.
Keenam, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam ghaib, misalnya
masjid, gereja, pura, wihara.
Ketujuh, Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan untuk mengatur kehidupan berkelompok-kelompok/bernegara, misalnya pemerintahan, partai politik. Kedelapan, Pranata sosial yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani manusia, misalnya pemeliharaan kesehatan dan kecantikan.
Hutan sebagai Ruang Kehidupan
Makna hutan bagi manusia dalam beragam pranata sosial tidaklah bisa dikatakan seragam. Bagi kebanyakan komunitas, menyatakan bahwa hutan sebagai sumber kehidupan, yang bermakna bahwa hutan menghasilkan sesuatu manfaat untuk pemenuhan sandang, papan dan pangan bagi manusia.
Bagi masyarakat lokal yang masih dalam budaya hidup meramu, maka hutan akan diambil manfaafnya dengan tidak merusak atau menebang hutan, tetapi hanya diambil hasil hutannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi secara domestik belaka, dan belum untuk tujuan dikomersilkan. Tradisi berburu binatang hutan dan ikan di perairan jugan masih menggunakan cara ramah lingkungan sehingga tidak mengancam punahnya suatu spesies mahluk hidup.
Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada masyarakat yang sudah mengenal pola pertanian berladang atau berkebun, cara pandang terhadap hutan juga mengalami pergeseran, hutan dianggap sebagai potensi ruang hidup yang boleh dibuka atau ditebang untuk dimanfaatkan lahannya menjadi perladangan atau perkebunan.
Pada kebanyakan komunitas, tradisi yang demikian itu dikenal dengan pola masyarakat ladang perpindah. Tradisi seperti ini masih belum sepenuhnya bersifat eksploitatif, karena ladang atau kebun yang dibuka akan kembali menjadi hutan sekunder, dan dari segi luas biasanya tidak dalam skala besar.
Seiring perkembangan kebutuhan sandang, papan dan pangan yang meningkat, cara pandang manusia terhadap hutan juga semakin berubah. Manusia mulai mengembangkan teknologi pertanian dan membuka lahan pertanian secra luas dan masif untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan global yang tinggi akan bahan baku pangan, perumahan, tekstil dan berbagai bahan baku lainnya. Hutanpun banyak dikonversi dan lahan digunakan untuk berbagai peruntukan manusia.
Era ini sering juga disebut dengan masa bercokolnya paham revolusi hijau, dan era berkembangnya pertanian monokultur skala besar dan padat modal. Berbagai kebijakan negara untuk menyokong revolusi hijau juga lahir, sehingga eksploitasi hutan dilegalkan asalkan memenuhi syarat-syarat dan perizinan yang dikeluarkan pemerintah. Karena itu, tidak heran jika karpet merah eksploitasi hutanbanyak diberikan untuk berbagai investasi skala besar, seperti hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.
Tarik Menarik kepentingan pemanfaatan hutan
Dalam rangka mengatur pemanfaatan hutan, pemerintah menetapkan status dan fungsi hutan yaitu status hutan negara dan hutan hak, dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi serta areal non hutan. Berbagai peraturan perundangan untuk menertibkan pemanfaatan hutan memberikan kewenangan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pemerataan keadilan dalam pemanfaatan hutan mulai menjadi perhatian pemerintah, karena selama Kemerdekaan Indonesia perijinan pemanfaatan hutan lebih banyak diberikan kepada investasi skala besar. Mulai tahun 2015, Pemerintahan baru di bawah Presiden Joko Widodo berkomitmen memberikan akses pemanfataan hutan melalui skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar, dan melalui skema reformaagraria barasal dari kawasan hutan mencapai 4 juta hektar.
Kendati demikian, mandat mulia yang diberikan kepada KLHK ini bila dilihat dari capaian pertahun 2022 masih jauh dari target. Menurut data yang dipublikasi KLHK sendiri, pencapaian pehutanan sosial baru mencapai 31,5% atau menjadi 40,1% jika memasukan peta indikatif hutan adat seluas 1,09 juta hektar. Angka pencapaian tersebut yang meliputi hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan kemitraan dan hutan adat. Jika menghitung priode pemerintahan presiden Joko Widodo yang tersisa 1 tahun lagi, maka dapat dipastikan pencapaian 12,7 juta hektar ini akan gagal dicapai oleh KLHK.
Kegagalan sejatinya bukanlah tanpa sebab, tarik menarik kepentingan kerap terjadi dilapangan. Kawasan hutan yang semula untuk perhutanan sosial telah berubah peruntukan, baik secara legal maupun ilegal. Peruntukan secara ilegal banyak ditemukan ketika UUCKP pasal 110A dan 110B memberikan ruang “pengampunan” pada kegitan usaha tanpa izin dalam kawasan hutan. Ketentuan teknis kedua pasal tersebut diturunkan dalam bentuk PP No. 24 tahun 2021.
Pelaksanaan PP oleh KLHK mencatat sekitar 3,3 juta hektar pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang harus diselesaikan dengan penerapan sanksi denda. Riau dan Kalimantan Tengah menduduki posisi teratas temuan pemanfaatan hutan tanpa izin, yaitu masing-masing 1,4juta hektar dan 800ribuan hektar.
Hentikan menyalahkan rakyat
Kawasan hutan dengan fungsi konservasi tidak luput dari perusakan, mengingat hutan produksi mayoritas telah beralih peruntukan menjadi konsesi perkebunan, hutan tanaman, pertambangan dan bentuk penguasaan lainnya. Konsesi tersebut mayoritas dikuasai korporasi yang telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan (IPKH), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) maupun izin pemanfaatan hasil hutan
kayu hutan alam/hutan tanaman (IPHHK HA/HT) secara resmi dari KLHK.
Konsesi skala besar-besaran, baik yang legal maupun ilegal inilah yang telah mengubah bentang alam hutan primer maupun sekunder yang tadinya merupakan habitat alami satwa-satwa endemik dan satwa dilindungi, seperti gajah, harimau, badak, dan sebagainya. Perubahan bentang alam yang dilegalkan, turut pula merubah pola pikir masyarakat sekitar hutan maupun yang ada dalam kawasan hutan. Masyarakat sekitar maupun dalam hutan juga tidak mau hanya jadi penonton konversi hutan besar-besaran, dan akhirnya
tergoda untuk membuka hutan secara luas, baik secara mandiri maupun dibantu pemodal.
Perubahan bentang alam juga mengakibatkan habitat dan wilayah jelajah satwa dilindungi hilang, dan menyebabkan adanya serangan atau konflik wilayah-wilayah yang telah menjadi ruang kelola masyarakat
lokal.
Untuk selamat dari ancaman serangan tersebut, masyarakat dengan terpaksa menyelamatkan asetnya dengan berbagai cara, seperti memasang jerat, meracuni atau memburunya dengan senjata tajam. Kemampuan masyarakat lokal membuat kegiatan mitigasi dan penanganan gangguan tidak bisa disamapakan dengan korporasi besar, karena masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan finansial untuk
membuat parit-parit gajah mengelilingi areal kebunnya.
Jadi, tidak pada tempatnya kalau ada pihak yang menyalahkan masyarakat lokal ketika ada gangguan satwa liar, seperti gajah dan harimau. Karena perubahan bentang alam besar-besaran dan masif justru dikakukan oleh pemegang izin IPKH, IPPKH maupun IPHHK HA/HT yang dikeluarkan KLHK, termasuk kegiatan usaha tanpa izin dalam kawasan hutan yang jumlahnya mencapai 3,3 juta hektar yang saat ini dalam proses “pengampunan” dengan pembayaran denda kepada KLHK berdasarkan mandat UUCK/Perpu UUCK dan
PP 24 tahun 2021.
Dengan demikian, maka kerusakan hutan dan bentang alam di Indonesia merupakan problem struktural, dan tidaklah bijaksana kalau ada pihak yang membebankan kesalahan kepada masyarakat lokal.